
SUKARNYA MEMASYARAKATKAN PENDIDIKAN BROADCASTING
SUKARNYA MEMASYARAKATKAN PENDIDIKAN BROADCASTING
– SEBUAH OPINI JUJUR
Oleh Ryandhika Rahman
Saat saya sekolah dulu sering sekali saya
mendengar ungkapan sakti yang bunyinya seperti ini "pendidikan adalah
modal utama membangun diri". Ungkapan yang semakin lama semakin saya amini
kebenarannya. Kemudian ketika saya mengenyam bangku kuliah di jurusan
komunikasi dan penyiaran saya mendapatkan jargon baru lagi, "Jika ingin
menguasai dunia, kuasai lah media." yang lagi-lagi setelah kian dewasa
saya memandang dan menjalani hidup dengan berbagai dinamika media, saya juga
semakin meyakini keabsahan jargon tersebut.
Lalu jika kedua ungkapan tersebut ternyata
sebegitu sahihnya, bagaimana jika keduanya dikombinasikan dalam satu kalimat
utuh? Pendidikan Media, atau pendidikan menguasai media, atau pendidikan
menyiarkan media, atau pendidikan tentang media? Apakah akan sangat meyakinkan
sebagai sebuah studi yang bukan hanya prestis tapi juga menjadi sebuah bidang
keilmuan yang menjanjikan peran besar bagi para pelakunya dalam mengarungi
ketatnya persaingan di era saat ini?
Mari kita bergeser ke sisi yang lebih familiar.
Media saat ini, khususnya digital bisa dibilang memberi pengaruh besar terhadap
tingkah laku masyarakat dunia, tak hanya di Indonesia. Begitu ada yang viral,
lalu 'digoreng' oleh media dengan berbagai bumbu yang sebenarnya poinnya hanya
itu saja namun bisa membuat sekian persen populasi masyarakat dunia apalagi
yang sempat mengakses informasi tentang itu, menjadi ikut terseret fenomena
yang disebarkan si media.
Masih ingat fenomena Om Telolet Om? Berbekal
kebiasaan anak-anak di salah satu daerah di Indonesia yang gemar berdiri di
pinggir jalan sembari menanti kedatangan bus lewat yang ketika datang para
anak-anak ini langsung dengan semangat berteriak 'Om Telolet Om' sebagai tanda
permintaan bunyi klakson khas dari bus tersebut yang biasanya akan dipenuhi
oleh sang sopir.
Hal tersebut kemudian dikemas oleh berbagai media
dengan berbagai macam sudut, diakses oleh masyarakat secara luas. Lantas apa
yang terjadi? Seperti yang sudah sama-sama kita tahu, hampir seluruh daerah di
Indonesia seolah keracunan fenomena ini, bukan hanya anak-anak, tapi juga orang
dewasa berdiri di pinggir jalan untuk meneriakkan hal yang sama ke tiap bus
yang lewat. Lebih menakjubkan lagi, hal ini bahkan sampai diikuti ke luar
negeri, mulai dari klub sepak bola ternama eropa, hingga para pesohor kenamaan
dunia. Begitupun dengan fenomena lainnya yang muncul dan sempat ramai.
Lantas apa poinnya?
Kita melihat dengan pasti bahwa media lah yang
menjadi sutradara akan semua kebisingan dan hal-hal viral ini. Jadi sudah bisa
disimpulkan sesakti apa media? Nah, bagaimana jika diciptakan sebuah pendidikan
yang khusus mempelajari bagaimana memahami dan mengorganisir media ini untuk
bukan hanya mengolah sesuatu yang viral tapi juga sesuatu yang bisa membangun
moral masyarakat?
Bagi kota-kota besar atau kota yang telah mapan
kemampuan berpikir masyarakatnya tentang pentingnya peran media maka jalur
pendidikan media menjadi sangat diidamkan dan menjelma sebagai salah satu
destinasi pendidikan favorit bagi mereka atau anak-anak mereka. Beda hal dengan
yang terjadi di kota-kota dengan kultur industri media yang 'tidak nampak' maka
jalur pendidikan media atau kita sebut saja jurusan broadcasting menjadi
jurusan studi yang begitu mudah dilupakan, apalagi jika dibandingkan dengan
jurusan yang 'tampak lebih hidup di masyarakat' seperti otomotif, mesin, tata
boga, dan sebagainya. Padahal jika boleh jujur, efek yang ditimbulkan media
bisa jadi sama besar dengan apa yang ditimbulkannya di kota besar, namun entah
mengapa hal itu belum juga mengangkat antusiasme masyarakat untuk menjadikan
jurusan Broadcasting sebagai tujuan studi yang layak untuk dipilih.
Saya mengatakan ini bukan tanpa sebab, saya
tinggal di Palangka Raya, kota yang konon katanya pernah menjadi impian Bung
Karno untuk jadi ibu kota Indonesia, kota yang diakui sebagai salah satu kota
dengan penataan ruang terbaik bahkan di Asia, kota terbesar di Kalimantan
Tengah, dengan lahan yang masih luas dan masih memiliki banyak potensi
keragaman industri kreatif meski dengan berbagai keterbatasan sarana dan pra
sarana. Di Kota ini saya menggantungkan mimpi saya dengan berkuliah di Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran bersama enam orang lainnya di angkatan saya.
Ya, anda tak salah baca, enam orang. Tujuh
bersama saya, itu pun di tengah semester kehilangan satu personil yang memilih
untuk pindah jurusan. Sebuah ironi, tentu saja. Ironi yang mungkin saja tak
hanya terjadi di kota saya, tapi juga beberapa kota lainnya. Ironi mengingat
betapa besarnya pengaruh media terhadap pola hidup manusia di zaman sekarang
namun di kota saya - setidaknya- orang sama sekali tak berpikir ranah ini layak
untuk disentuh sebagai tujuan pendidikan atau profesionalisme.
Jika kemudian yang menjadi dalih atas semua ini
adalah karena di kota saya dan kota-kota lain yang bernasib sama tidak memiliki
industri media massa yang kuat, seperti televisi lokal, media massa lokal,
radio dan sebagainya yang bisa hidup mapan dan menghasilkan profit menjanjikan
layaknya di kota seperti Jabodetabek, Surabaya, Jogja, Makassar, Medan, Bandung
dan lain-lain maka saya dengan yakin menyanggah itu semua. Seandainya kita
masih hidup di era tahun 90an atau mungkin di 2000an awal alasan tersebut bisa
jadi memang masuk akal. Pada era tersebut media yang bisa diakses masyarakat
hanya itu-itu saja, kalau bukan televisi, ya radio, atau media cetak, dan
pilihannya terbatas. Tapi saat ini zaman sudah jauh berkembang, bahkan
bisa jadi jauh berkembang ketimbang manusianya. Kita tak perlu lagi sebuah
stasiun televisi besar dengan pemancar, dengan kabel transmisi, dengan channel
UHF, studio besar, alat-alat canggih, dan sebagainya untuk memproduksi sebuah
konten informasi. Hanya berbekal internet yang bahkan bisa dibeli dengan
harga 10.000 perak dan kamera handphone minimal, kita sudah bisa menyebarkan
informasi yang kita produksi ke seluruh belahan dunia, bisa mendapatkan income
hingga jutaan atau bahkan ratusan juta. Jika dulu saat saya melamar jadi
penyiar radio saya harus seleksi hingga hitungan minggu dan bersaing dengan
ratusan orang, sekarang berbekal aplikasi podcast dan mik standar semua orang
bisa berbicara dan mempublishnya ke dunia luar.
Masih ingat bagaimana sebuah akun twitter bernama
Zarry Hendrik dengan modal cuitan dengan 140 karakter bisa membawanya menjadi
salah satu penulis ternama dengan penghasilan ratusan juta rupiah tanpa harus
repot-repot mengirimkannya dulu ke berbagai media cetak? atau bagaimana Raditya
Dika angkat nama lewat curhatan isengnya lewat blog pribadinya? apakah mereka
semua perlu media mainstream seperti penerbit besar dan sebagainya? Tidak kan?
Tapi mereka bisa sukses mendulang gelimang rupiah dan tentu saja ketenaran.
Hal ini sebenarnya memicu fenomena yang lebih
serius, yaitu semakin bebasnya orang akan kreasi dan bukti eksistensi diri
sehingga kerap melupakan batas norma dan tanggung jawab sosial. Sehingga
terjadi yang sering kita temukan konten yang seharusnya tidak layak dipublish
untuk umum atau bahkan tidak layak untuk dilakukan, mulai dari video viral
bagi-bagi sampah, sosial eksperimen atau prank kepada ojek online, video
kekerasan, tulisan yang sarat muatan kebencian, dan hal-hal lain yang parahnya
bisa dengan mudah diakses oleh generasi mudah bahkan anak-anak yang belum mengerti
apa itu arti tanggung jawab. Ini tentu saja berdampak pada moral para
penonton yang mengakses konten-konten seperti itu, hal-hal negatif jadi semakin
cepat menyebar tanpa bisa dikontrol karena saking cepatnya arus
informasi.
Di saat inilah harapan pada para generasi dengan
pengetahuan dan kemampuan broadcaster yang didapat dari jalur pendidikan
bertumpu. Sebagai orang yang tidak hanya diajari untuk mengenal tapi juga
memilah dan mengorganisasi media dengan segala kontennya, tentunya mereka diharapkan
mampu menetralkan informasi-informasi negatif dan memolesnya dengan
konten-konten kreatif yang jauh lebih positif dan memberi inspirasi bagi orang
lain.
Namun sekali lagi, tak banyak orang yang aware
terhadap pendidikan broadcasting ini - setidaknya di kota saya - karena ada
juga yang beralasan jenjang kerjanya tak jelas, peluang kerjanya masih sempit,
modal kerjanya mahal, dan sebagainya. Padahal seandainya kita menyadari bahwa
kita selalu butuh mereka para lulusan broadcasting ini, bukan hanya untuk membuat
konten informasi untuk massa, tapi juga sesederhana mendokumentasikan berbagai
kegiatan kita. Saya punya banyak teman yang bekerja di bidang videografi yang
harga jasa mereka untuk sehari rekaman video pernikahan aja minimalnya 2-4 juta
rupiah, untuk video lain beda lagi harganya. Atau teman saya yang seorang copy
writter yang mengaku bisa menghasilkan 1,5 - 3 juta rupiah untuk setiap tulisan
yang dipesankan kepadanya. Itu semua adalah bukti nyata betapa ternyata
pendidikan Broadcasting bukan hanya penting dalam mengontrol konten informasi
yang beredar di masyarakat tapi juga menyiapkan para generasi yang siap
berkarya positif, kreatif, dan tentu saja memiliki nilai jual tinggi di
industri kerja.
Apa yang saya tulis tentang rendahnya minat orang
terhadap pendidikan broadcasting ini bisa jadi tak berlaku di beberapa daerah,
terutama di daerah yang kultur industrinya tak melulu tentang menjadi PNS atau
pekerjaan yang 'terlihat menjanjikan' karena di Banjarmasin pun sebagai salah
satu kota terdekat dengan kota saya tinggal jurusan broadcastingnya menjadi
primadona, karena mungkin pola pikir masyarakatnya sudah jauh lebih terbuka
tentang betapa besarnya bidang ini untuk dieksplorasi.
Hal yang saya selalu harapkan bisa menjadi magnet
yang juga terjadi di kota saya, Palangka Raya, dan kota-kota lain di Kalimantan
Tengah dan daerah lain yang bernasib sama. Karena hanya di tangan orang-orang
terpelajar dan berpendidikan sejalur lah moral masyarakat yang kadung terbentuk
dari informasi yang mereka serap bisa lebih dikontrol ke arah yang lebih
postif.
Sekali lagi saya ingat ungkapan agung itu,
"Jika ingin menguasai dunia, maka kuasailah media."
Namun, jangankan menguasai, menyentuhnya pun kita
tak akan bisa jika terlalu segan atau takut untuk memulai.
Sekian.
(Tulisan ini sudah pernah dimuat di Kompasiana
pada 16 Maret 2021)
*Penulis adalah salah satu tenaga pendidik di SMK
Muhammadiyah Palangka Raya

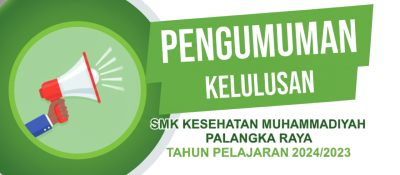

-100x100.jpeg)



-100x100.jpeg)
-Photoroom-400x185.png)